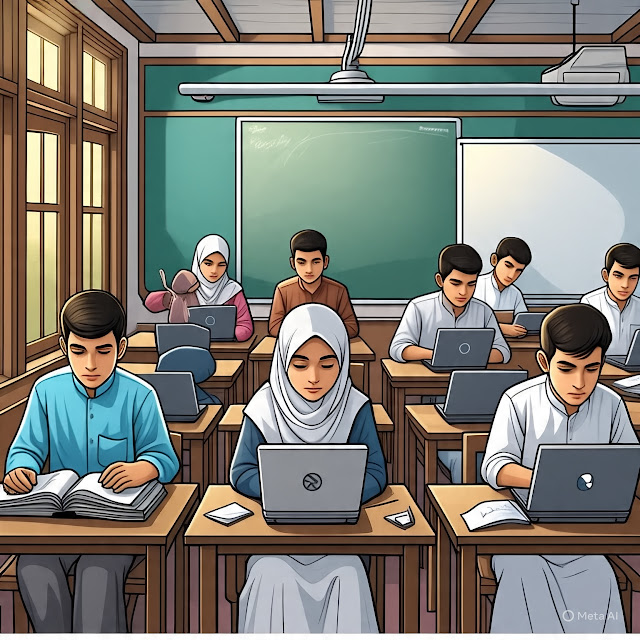Oleh: Syamsul Kurniawan
Di tengah perhelatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ),
muncul sebuah cabang baru yang dalam beberapa tahun belakangan mulai
diperkenalkan: Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an (KTIQ). Sebuah istilah yang
barangkali terdengar sunyi di tengah riuh lantunan tilawah. Tapi justru dari
kesunyian itulah, pikiran yang hidup mungkin menemukan ruangnya.
KTIQ tidak menggaungkan suara, melainkan menggugah nalar. Ia
tidak berpijak pada hafalan, melainkan pada kegelisahan. Bahwa Al-Qur'an bukan
hanya untuk dibaca, tetapi juga untuk dipikirkan, ditafsirkan, dipertanyakan.
Namun ketika ajang itu berlangsung, karya-karya yang lahir
justru memunculkan tanya yang lain. Mengapa begitu banyak naskah yang terasa
menjauh dari inti Al-Qur’an? Mengapa ayat-ayat hanya muncul sebagai pelengkap,
bukan sebagai pusat?
Tema sudah disiapkan, ayat baru dicari. Narasi sudah dibentuk, teks suci hanya dikutip untuk membenarkan. Maka mengemuka sebuah pendekatan yang—meskipun tak lazim diakui secara terbuka dalam dunia akademik, namun kerap digunakan—dan dalam konteks ini, terasa dangkal: "cocokologi".
KTIQ, yang seharusnya menjadi ruang hidup bagi pemikiran
yang bersumber dari Al-Qur’an, berubah menjadi cermin dari kebiasaan lama:
menjadikan teks suci sebagai dekorasi akademik. Kata-kata suci tidak lagi
mengguncang. Ia diseret ke dalam logika birokrasi ilmu.
Tak masalah sebenarnya, membahas tema seperti krisis
lingkungan, pergeseran keberagamaan, atau ketahanan keluarga. Tapi seperti doa
yang dilafalkan tanpa hati, tema-tema ini kehilangan denyut jika tidak dibaca
dengan sungguh-sungguh.
Tulisan menjadi datar. Tidak menggugah. Tidak menyisakan
ruang untuk kegelisahan atau bahkan perdebatan. Ia hadir sebagai kepatuhan yang
rapi, bukan sebagai keberanian yang resah.
Dalam sejumlah naskah yang ditulis, naskah yang mengangkat
hukum Islam justru lebih banyak mengutip UU dan pasal-pasal negara. Ayat
Al-Qur’an datang belakangan. Ia hadir bukan sebagai pemantik, tetapi sebagai
formalitas. Hal serupa terjadi pada naskah-naskah yang membahas isu kearifan
lokal. Dalam beberapa tulisan, kearifan lokal digambarkan seolah begitu dekat
dengan nilai-nilai Al-Qur’an. Namun bagaimana kedekatan itu dibangun, dari mana
kesesuaiannya diperoleh, dan apa dasar validitas pembuktiannya—tidak dijelaskan
secara memadai. Akhirnya, yang tampak bukan sintesis yang kokoh, melainkan
jembatan rapuh yang dipaksakan. Ia hadir bukan sebagai pemantik, tetapi sebagai
formalitas.
Barangkali ini bukan salah penulis sepenuhnya. Barangkali
kita memang belum cukup membiasakan cara berpikir yang menjadikan Al-Qur’an
sebagai ruang dialog. Bukan menara gading yang harus disembah, tetapi ruang
kosong yang harus dihuni.
Tulisan-tulisan itu belum sepenuhnya menyadari: bahwa karya
ilmiah yang berangkat dari Al-Qur’an seharusnya menantang. Bukan hanya
menjelaskan apa yang sudah diketahui, tetapi mengusik kenyamanan apa yang kita
kira sudah benar.
Dalam ruang itulah, gagasan Habermas (1991) menjadi relevan.
Ia membayangkan ruang publik sebagai arena rasional. Tempat argumen diadu,
bukan dipoles. Tempat otoritas diganti nalar.
Jika Al-Qur’an dibawa ke ruang itu, maka ia pun harus tahan
diuji. Ayat tak bisa hanya dikutip. Ia harus dihadirkan: dalam konflik makna,
dalam lapisan tafsir, dalam konteks sosial yang rumit.
KTIQ seharusnya menghidupkan itu. Bukan sebagai ajang lomba
biasa, melainkan sebagai bentuk keterlibatan pemikiran terhadap Al-Qur’an
dengan denyut zaman. Tapi untuk itu, dibutuhkan keberanian berpikir. Dan
ketelitian membaca.
Diperlukan Novelty
Novelty bukan jargon. Ia adalah nafas dari sebuah pemikiran.
Ia bukan soal berbeda, tapi soal berani. Berani bertanya dengan cara yang tak
biasa. Berani membaca dengan kecurigaan yang sehat.
Namun pada beberapa naskah, tema-tema yang diangkat terasa
terlalu akrab. Ketahanan keluarga, transformasi digital—topik-topik yang
seharusnya menggugah, justru menjadi pengulangan.
Mereka ditulis bukan karena kegelisahan, tetapi karena
kedekatannya dengan tema populer. Maka, apa yang ditawarkan menjadi lemah.
Perspektif segar hilang. Tafsir baru tidak hadir.
Padahal novelty bisa lahir dari sudut yang sederhana.
Seperti bertanya, bukan “apa ayat tentang keluarga”, tetapi “bagaimana keluarga
ideal menurut Al-Qur’an hidup dalam masyarakat yang cair?”
Atau “mengapa ayat waris terasa asing dalam logika keadilan
gender masa kini?”
Kebaruan muncul bukan karena ayatnya baru, tapi karena cara
pandangnya lain. Seperti cermin yang sama, tapi sudut pantulnya berbeda.
Howard Becker menulis dalam Tricks of the Trade
(1998), bahwa pertanyaan yang baik sering kali bukan “mengapa”, tapi
“bagaimana”. Karena “bagaimana” membuka narasi, sedang “mengapa” menutupnya
dengan penjelasan prematur.
Becker menyarankan agar kita menggali celah antara dasein
dan dassollen. Antara yang ada dan yang seharusnya ada. Di sanalah letak
keilmuan: di antara yang belum selesai.
Maka KTIQ pun bisa bergerak di celah itu. Menyigi apa yang
tak terlihat. Menggugat yang terlalu mapan. Meragukan yang terlalu diamini.
Bagaimana ayat-ayat tentang amanah diterapkan di tengah
krisis integritas? Bagaimana makna keluarga tetap bertahan dalam generasi
fatherless?
Semua itu adalah pintu masuk. Bukan ke surga jawaban, tetapi
ke neraka pertanyaan. Dan di situlah ilmu seharusnya tumbuh.
Namun novelty tak lahir dari kemauan saja. Ia butuh metode.
Ia butuh kejujuran berpikir. Dan yang lebih sulit: ia butuh kesediaan untuk
tidak selalu tampak pintar.
Istilah seperti “episteme profetik” kadang muncul, tapi
hanya sebagai kosmetik. Indah di lidah, kosong di makna. Kata-kata menjadi
pertunjukan, bukan pengungkapan.
Habermas menekankan, bahwa dalam ruang publik, argumenlah
yang berdaulat. Maka dalam KTIQ pun, bukan jumlah ayat yang menentukan, tapi
kekuatan mengaitkannya dengan kenyataan.
Ayat-ayat suci tidak pernah kehabisan tafsir. Tapi tafsir
bisa kehabisan nyali. Dan karya tulis yang menempatkan Al-Qur’an sebagai sumber
utama gagasan, adalah yang memiliki keberanian itu.
KTIQ bukan panggung. Ia mestinya menjadi percakapan. Antara
teks dan konteks. Antara nalar dan wahyu. Antara zaman dan zikir.
Ia bukan ajang adu pintar. Ia adalah ruang untuk jeda. Untuk
berpikir ulang. Untuk bertanya pelan-pelan.
Sebab di balik ayat, selalu ada dunia. Dan di balik dunia,
selalu ada ayat.
Menulis karya ilmiah dengan dasar Al-Qur’an bukan perkara
mencari jawaban. Tapi memelihara kegelisahan. Agar kita tak terlalu cepat
percaya. Agar kita tak terlalu lama diam.
Al-Qur’an bukan benda mati. Ia hidup sejauh kita membacanya
sebagai yang belum selesai.
Dan dari yang belum selesai itulah, karya-karya baru bisa
lahir. Tak harus sempurna. Cukup jujur.
Mungkin itulah jeda yang kita perlukan. Sebelum kita kembali
melangkah.***